
KARANGWUNI
“Yen Bupati ora tegas, iso repot ngadhepi wargane”
(Kalau bupati tidak tegas, bisa repot menghadapi warga)
-Komentar warga Karangwuni dalam Pertemuan Warga 25 Mei 2004,di sekretariat FKMK-
Desa ini terletak di pesisir selatan Kabupaten Kulonprogo, tepatnya di sebelah timur Pantai Glagah. Menghuni 6 dusun, penduduknya bekerja sebagai petani lahan pantai, dengan menanam cabai, semangka dan sayur-sayuran di atas lahan pantai yang lebih sering disebut dengan Paku Alam Ground (PAG). Lahan inilah yang sering menjadi pokok sengketa antara warga dan negara. Pasalnya, sudah puluhan tahun warga menggarap lahan tersebut, mengubahnya dari lahan tidur yang tandus, kering dan gersang menjadi lahan hijau sekarang ini. Namun, meski sudah puluhan tahun menggarap lahan, mereka tidak mendapatkan legalisasi atas status tanah yang mereka garap. Orang menyebutnya, tidak ada “surat kekancingan” untuk status warga penggarap lahan. Hal ini terjadi karena adanya pengecualian status tanah dalam UU
Pokok Agraria untuk beberapa kategori, diantaranya adalah Sultan Ground (SG) dan PAG di wilayah DI Yogyakarta. Warga sebetulnya mengharapkan agar penggarapan berpuluh tahun tersebut bisa menjadi dasar proses pengubahan status tanah menjadi objek hak. Namun, bukannya proses yang menggembirakan petani, yang muncul justru kebijakan untuk menjadikan lahan untuk program yang dipastikan mengancam keberadaan petani. Pada tahun 90-an, pemerintah berencana membangun lapangan golf di kawasan pantai tersebut. Rencana ini ditentang oleh warga penggarap lahan pasir tersebut karena proyek itu mengancam satu-satunya sumber penghidupan mereka. Akhirnya, rencana pembangunan lapangan golf ini dibatalkan dan dipindah ke tempat lain.Tahun 2004 ini, pemerintah kabupaten melalui Kepala Desa kembali melontarkan rencana menjadikan lahan pesisir untuk kawasan transmigrasi. Program yang bernama Transmigrasi Ring 1 ini akan melanjutkan program serupa yang sudah berjalan di desa Bugel -desa di sebelah desa Karangwuni- yang disediakan sebagai kawasan relokasi warga korban bencana longsor di Perbukitan Menoreh, bagian utara Kulon Progo.
Pemerintah juga berjanji memberi beberapa kapling rumah bagi petani penggarap lahan pesisir. Namun, warga menolak rencana pemerintah tersebut, karena yang dibutuhkan warga adalah kejelasan status, bukan rumah seperti yang dijanjikan pemerintah. Warga menunjuk pemukiman Bugel yang ditinggalkan warga pindahan dari Menoreh, sebagai bukti bahwa program tersebut salah sasaran, tidak melibatkan masyarakat dan tidak menjawab kebutuhan utama warga.Saat ini, warga kawasan pesisir Karangwuni, bersama-sama dengan warga desa Karangsewu dan Banaran -dua desa lain yang sangat mungkin terkena program transmigrasi Ring 1- sedang berupaya bersama-sama memperjuangkan pengukuhan status petani penggarap dan sekaligus menolak program yang meminggirkan petani, termasuk program Transmigrasi Ring 1.
Akhir Mei kemarin, warga menyelenggarakan hearing dengan Pemerintah kabupaten Kulon Progo di Ruang Serba Guna Desa Banaran yang diikuti 350 petani penggarap. Hearing ini dimaksudkan untuk mendesak Pemkab segera memenuhi kebutuhan legalisasi tanah PAG daripada mengedepankan proyek yang justru meminggirkan petani. Sayangnya, dalam pertemuan tersebut Bupati yang sudah menyatakan bisa hadir, batal datang dan hanya diwakili oleh Asisten Sekda. Karenanya, hingga catatan ini ditulis, proses konsolidasi jaringan yang diberi nama Komunitas Masyarakat Pesisir masih terus dilakukan, dan serangkaian aktivitas memperjuangkan hak petani penggara juga terus berjalan.
Sumber: Laporan lapangan dan workshop

BANARAN
“Yen anggarane cilik, kapan sehate balita?”
(Kalau anggaran sedikit, kapan sehatnya balita?)
-Komentar warga dusun Sidorejo dalam Pertemuan kelompok Tani Maju, 15 Mei 2004, di Sidorejo-
Mungkin mengagetkan, tapi inilah fakta tentang kecilnya anggaran posyandu di banyak desa, termasuk di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kulonprogo. Pada tahun 2002, alokasi anggaran dari Pemerintah Desa hanya 2500 per posyandu per bulan. Jumlah ini kemudian dinaikkan pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp 10000,- per posyandu per bulan.
Dengan perkiraan ada 40 balita per dusun, maka mereka masing-masing akan mendapatkan bagian anggaran sebesar Rp 250- per bulan. Bisa apa dengan uang sekecil itu? Para ibu hanya bisa membeli satu tempe atau tahu goreng untuk balitanya. Jadi, jangan membayangkan anak-anak balita mendapatkan semangkuk bubur kacang hijau, apalagi ditambah segelas susu. Pada sisi lain, pemerintah kabupaten tidak menganggarkan apapun. ada anggaran yang dimaksud. Katanya, posyandu adalah program dari, oleh dan untuk masyarakat. Jadi, wajar bila masyarakat ikut berswadaya untuk penyelenggaraan posyandu.
Fakta tersebut juga menunjukkan betapa kecilnya perhatian pemerintah yang diwujudkan melalui program dan anggaran pembangunan yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Menambah panjang daftar derita masyarakat yang tidak bisa terlibat dalam memutuskan kebijakan anggaran, dampak yang dirasakan kaum perempuan dan anak-anak, juga semakin berat. Alih-alih dapat kemanfaatan, yang terjadi justru pengalihan beban dan urusan, dari negara menjadi urusan perempuan.
Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan dan masyarakat miskin untuk memperjuangkan agar kepentingannya diakomodir dalam kebijakan anggaran? Mengadakan pertemuan, merumuskan masalah dan menyusun rencana advokasi, serta membangun dialog dengan pengambil kebijakan anggaran baik di tingkat desa maupun kabupaten, adalah beberapa langkah yang dilakukan komunitas Tani Maju, sebuah kelompok petani di pesisir Desa Banaran, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Trisik. Hasilnya, untuk Tahun 2004 ini, Pemerintah Desa akan menaikkan alokasi anggaran posyandu menjadi Rp 20.000,- per posyandu per bulan. Selain itu, Pemdes juga akan menambah alokasi dana yang akan dikelola dusun untuk pembangunan kebutuhan spesifik dusun, serta akan memangkas pos-pos anggaran yang tidak menunjang peningkatan kesejahteraan warga. Menurut Teguh, warga Sidorejo, ini merupakan pengalaman baru yang berharga baginya. Menurutnya , “…Lagi saiki diajak ngrembug kebutuhan anggaran masyarakat karo Pemdes lan BPD” (Baru sekarang ini diajak diskusi kebutuhan anggaran masyarakat oleh Pemdes dan BPD). Mudah-mudahan, proses ini bisa terus berlanjut dalam mewujudkan kebijakan anggaran yang partisipatif dan berpihak pada masyarakat.
Sumber: laporan lapangan dan workshop

WONOLELO
“Pamong-pamong di kelurahan saya tidak pernah memberi tahu anggaran-anggaran yang ada di kelurahan”
“Kepala dusun itu baik terhadap warga, tapi tidak transparan terhadap pengelolaan uang”
-Rekaman proses Pelatihan Advokasi Anggaran Bantul, Parangtritis, 16-18 April 2004-
Pernahkah Anda tahu berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah? Biarpun pertanyaan ini diajukan kepada masyarakat, jawaban yang serupa dengan lontaran diatas, bisa jadi akan kita temui. Ini menunjukkan bahwa yang namanya keterbukaan dan transparansi anggaran, masih menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Hal yang sama juga terjadi di desa Wonolelo, kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
Wonolelo adalah salah satu desa miskin di Kabupaten Bantul. Terletak di sisi timur wilayah Kabupaten Bantul, desa ini berbatasan langsung dengan kecamatan Dlingo. Sebagaimana kawasan pegunungan kapur lainnya, persoalan minimnya sarana dan prasarana publik, pendidikan rendah dan air bersih adalah sebagian dari sederet masalah utama desa ini. Kondisi ini semakin diperparah dengan dengan ketidakterbukaan proses penyelenggaraan pemerintahan dan minimnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, masalah-masalah dasar masyarakat, justru sering terlupakan dan tidak tersentuh pembangunan.
Salah satu masalah dasar tersebut adalah masalah air bersih. Biarpun sudah bertahun-tahun warga mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih, tidak ada anggaran dan program yang sampai ke masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akhirnya, pada pertengahan tahun 2002, warga dusun Ploso yang tergabung dalam Kelompok Ngudi Mulyo, mengajukan usulan pembangunan bak penampung dan saluran air bersih hingga ke rumah tangga. Dengan usulan ini, warga berharap supaya tidak perlu lagi bersusah-payah berjalan jauh menuruni bukit kapur yang terjal untuk mendapat sepikul air dari mata air di sebelah timur desa. Usulan ini diajukan kepada Pemerintah Kabupaten dan Propinsi melalui Dinas Kimpraswil serta kepada DPRD.
Usulan ini didapat setelah mereka merumuskan kebutuhan dasar warga. Untuk memperkuat usulan, warga melengkapinya dengan peta desa, jumlah KK yang membutuhkan sarana air bersih, kebutuhan material untuk pembangunan sarana air bersih hingga debit air dari mata air yang diusulkan warga. Untuk mengukur debit air, warga menggunakan jerigen minyak yang dihitung per detik untuk mengetahui debit air dari sumber mata air tersebut. Usulan ini juga dilengkapi dengan hitungan anggaran yang dianggap memadai untuk kebutuhan tersebut. Akhirnya, usulan warga dipenuhi pemerintah dengan pencairan anggaran sebanyak Rp 300 juta, dan kebutuhan warga akan air bersih tercukupi.
Di tingkat desa, persoalan keterbukaan anggaran desa juga menjadi agenda kegiatan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Ngudi Mulyo dan Ngudi Makmur ini. Berawal dari aktivitas diskusi masyarakat di dua dusun, yaitu Cegokan dan Wonolelo, proses mengkritisi anggaran desa kemudian juga melibatkan dusun-dusun lain di desa Wonolelo. Salah satu temuan menarik yang terungkap dari proses ini adalah dalam mengkritisi LPJ APBDes Wonolelo 2003. Warga mencatat beberapa persoalan yang mereka temukan, antara lain:
- Di anggaran ada anggaran pembangunan jalan dusun Cegokan sebesar Rp 8.750.000,-. Tapi, menurut kalkulasi warga, dana yang turun tidak sebesar itu.
- Kasusnya juga sama untuk pembangketan Cegokan sebesar Rp 27.000.000,-
- Pengambilan air dari Delingo tidak ada realisasinya
- Rehab balai desa tidak ada perincian dananya, dan yang direhab hanya genteng
Beberapa catatan inilah yang kemudian mereka ajukan baik kepada Pemdes maupun BPD, dan warga meminta agar LPJ direvisi sehingga semua uang bisa dipertanggung-jawabkan kepada publik. Bagi masyarakat, mendorong keterbukaan itu sangat penting. Sedikit atau banyak, yang namanya uang rakyat tetap harus dipertanggung-jawabkan.
Perempuan Bisa Bersuara Berbeda
Ada baiknya menyingkirkan anggapan bahwa perempuan desa identik dengan sikap pasrah, tidak kritis, dan tidak bisa bersuara. Bila sekali waktu mengikuti pertemuan Forum Komunikasi Perempuan (FKP) Cegokan, kita akan melihat spontantaninat dan keterbukaan mereka ketika membicarakan persoalan sosial yang mereka temukan. Simak saja lontaran mereka mengenai kinerja pelayanan pemerintah;
“Suntik di Bu Bidan sudah dilakukan tiap tiga bulan, bayar Rp 10.000,- Tapi, gagal terus. Jadi, ya hamil lagi, Mbak”
“Boro-boro untuk menyediakan susu balita, wong uang untuk bikin bubur kacang hijau psyandu saja nggak ada”
“Sudah tahunan jualan sayuran, tapi ya tidak tambah besar. Perhatian dari pemerintah? Ya, nggak ada. Semua jalan sendiri”
Kelompok yang baru seumur jagung ini -berdiri April 2004- juga merumuskan tindakan yang kemudian dilakukan dalam mengadvokasi persoalan tersebut. Menganalisis masalah, menuangkan dalam sikap dan usulan, serta membangun dialog dengan pejabat atau instansi terkait. Usulannya singkat dan sederhana, apa adanya, namun cukup berisi. Maklum saja, mereka bukan perempuan dari kelas terdidik. Mayoritas berpendidikan SD, sebagian ibu rumah tangga dan sebagian lagi pedagang sayur keliling kampung. Itulah gambaran perempuan dusun miskin yang masuk dalam wilayah desa Wonolelo, kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.
Hasilnya, Juli 2004, Pemerintah mengucurkan Rp 22 juta kredit lunak kepada perempuan pedagang kecil anggota FKP. Selain itu, pemerintah melalui Puskesmas juga mencairkan seluruh dana posyandu lansia sebesar Rp 50.000,- per bulan. Sebelumnya, Posyandu hanya menerima Rp 10.000,- per bulan, tanpa mendapat keterangan mengenai alokasi dana yang lain. Kebijakan yang lain yang juga sangat penting adalah adanya pelayanan KB gratis (spiral dan susuk) kepada 26 perempuan Cegokan.
Namun, capaian itu bukannya tanpa rintangan. Sebelumnya Kecamatan dan Puskesmas yang merasa dilangkahi dan tercoreng mukanya menanggapi upaya warga secara negatif. Mbak Kamti, ketua FKP, menuturkan masa-masa berat yang ia lalui ketika diminta menghadap Camat. Selama tiga jam, sendirian ia diminta menjelaskan apa yang dimaui oleh kelompok perempuan desa ini, siapa saja mereka, dan adakah pihak dari luar yang menunggangi kelompok ini. Bagi seorang perempuan desa, proses seperti ini lebih pas disebut sebagai interogasi, daripada dialog. Ia mengaku mengalami tekanan batin dan trauma sampai beberapa waktu setelah peristiwa tersebut.
Namun, ia tidak putus harapan. Ia mengundang kembali ibu-ibu, yang sekarang sudah mencakup hampir semua dusun di desa Wonolelo, serta beberapa desa di sekitarnya. Ia menceritakan pengalaman tersebut dan mengajak untuk mencari jalan keluar bersama. Pro dan kontra, semangat dan ketakutan serta harapan, mewarnai pertemuan tersebut. Biarpun begitu, forum menyepakati untuk mengundang pemerintah guna berdialog dengan kelompok perempuan tersebut. Akhirnya, beberapa waktu setelah dialog, beberapa kebijakan diatas dikeluarkan pemerintah. Walaupun kecil dari segi nominal dana, kemanfaatan buat mereka sangatlah besar. Pengalaman ini juga mengajarkan bahwa setiap perempuan punya hak untuk bersuara, apalagi yang menyangkut urusannya perempuan. Dan, hal itu bisa dilakukan kalau perempuan bersatu dan terorganisir.
Sumber: Laporan lapangan dan workshop
Seloharjo
Terletak di Kabupaten Bantul, Seloharjo adalah salah satu desa termiskin di Kecamatan Pundong, dengan sarana fisik yang belu mencukupi seluruh kebutuhan warga desa tersebut. Secara geografis, desa ini terbagi menjadi dua wilayah; dataran rendah yang berada di sepanjang jalur Kali Opak dan wilayah berbukit-bukit di belakangnya. Berbatasan dengan Selopamioro, Kecamatan Imogiri, desa ini ditinggali oleh penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai buruh bangunan, pekerja lepas perkebunan tebu, tukang becak, pedagang keliling dan penambang pasir. Penduduk tersebar di 16 pedukuhan dengan 40 sampai 55 keluarga miskin per pedukuhan.
Sebagaimana penduduk pedesaan di kawasan selatan Yogyakarta, warga Seloharjo harus bertahan di lahan kering tadah hujan. Kelangkaan sumber air dan tidak adanya fasilitas air bersih, penduduk sangat mengandalkan air Kali Opak dan mata air yang jumlah maupun debitnya sangat terbatas.
Terhitung sejak Mei 2004, IDEA bekerja di Seloharjo bersama penduduk di dusun Dermojurang dan Karangasem. Sebagai wilayah subjek program yang baru pertama kali berhubungan dengan IDEA, penduduk Dermojurang dan Karangasem baru mulai mengorganisir diri untuk bekerja secara kolektif mencari pemecahan persoalan-persoalan kebutuhan dan hak-hak dasar melalui anggaran daerah.
Sumber: Laporan lapangan
Selopamioro
Dusun Jetis. Terletak di pinggiran Kali Oya, dusun Jetis diapit oleh perbukitan kapur dan sungai. Topografi dusun ini berbukit-bukit yang sulit ditaklukkan. Untuk membangun rumah, penduduk harus memecah bebatuan dan membabat perbukitan. Lahan yang kering dan sumber air yang langka memaksa sebagian besar penduduk dusun Jetis bekerja di luar sektor pertanian sebagai buruh bangunan. Akibatnya, penduduk laki-laki sangat sedikit yang tinggal di dusun itu.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga Jetis mencoba mengalirkan air dari sumber yang cukup jauh dari pemukiman. Namun, itupun masih jauh dari mencukupi karena debit air yang memang sangat rendah. Kesulitan yang sama dialami penduduk yang ingin menggarap lahan pertanian -sebagian di atas tanah pelungguh dengan sewa-karena sumber air pertanian hanya bisa didapat dengan menimba dari sungai dan memikulnya ke ladang di pebukitan sepanjang sungai. Sumbangan pompa air dari tokoh partai politik setempat tidak mampu melayani seluruh petani jetis karena pengoperasiannya hanya bisa dilakukan oleh salah seorang pejabat desa yang tinggal di Jetis.
Dusun Kedungjati. Terletak di sudut timur desa Selopamioro, dan berbatasan langsung dengan kecamatan Playen, Gunungkidul, dusun Kedungjati hanya bisa dijangkau melalui jalan setapak selebar 1,5 meter. Jalan yang baru selesai dibuat setahun lalu itu “menempel” di tebing sepanjang sungai dan tidak mungkin dilewati kendaraan roda empat.
Menghuni 4 RT, 126 keluarga yang tinggal Jetis belum mendpatkan aliran listrik secara memadai sekalipun mereka sudah mengeluarkan uang untuk mendapatkan sambungan distribusi. Sebagian besar warganya tidak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian melainkan bekerja sebagai buruh bangunan. Tidak ada pengairan samasekali untuk lahan pertanian, kecuali menunggu turunnya hujan. Dalam kondisi demikian, sebagian besar penduduk laki-laki bekerja sebagai buruh bangunan.
Munthuk
Dusun Nglingseng. Terletak di sisi timur desa Munthuk, dusun Nglingseng dihuni oleh penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai petani lahan kering dan pembuat kerajinan bambu. Dengan pendidikan tertinggi penduduk rata-rata SD, warga dusun ini menjadi penerima terbesar jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin), sekalipun kriterianya ditetapkan secara tidak konsisten oleh perangkat desa.
Seperti tetangga mereka di Selopamioro, sebagian penduduk Nglingseng juga menerima beras pemerintah untuk masyarakat miskin (raskin). Jatah untuk 36 keluarga dibagi rata untuk 108 keluarga sehingga jatah masing-masing keluarga menjadi 3 kg per bulan dengan ongkos Rp 5.000.
Meskipun dengan keterbatasan di sana-sini, penduduk masih harus menanggung beban pembangunan jalan secara swadaya; di RT 5 tiap keluarga dibebani Rp 160.000 dan Rp 100.000. Sedangkan penduduk RT 6 dibebani lebih besar lagi, Rp 200.000 dan Rp 400.000 per keluarga. Itu belum termasuk pengadaan bantalan jalan sepanjang 3 kilometer dan memberi makan operator mesin giling sewaan dari Dinas Kimpraswil.
Sekalipun ada sumber air yang bisa diakses, sebagian penduduk menggantungkan diri pada penampungan air hujan. Bak penampungan air dari mata air belum dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sedangkan untuk pertanian, penduduk mengandalkan air curahan hujan. Penduduk Nglingseng, bersama-sama dengan Tangkil adalah penerima terbanyak dana jaring pengaman sosial untuk kesehatan (JPKM, kartu sehat).
Dusun Seropan I. Wilayah ini dihuni oleh 125 keluarga dengan 46 keluarga miskin. Problem air bersih cukup serius karena ketersediaan yang sangat minim. Penduduk mendapatkannya melalui selang plastik yang menghubungkan sumber air berdebit sangat rendah dengan bak penampungan kolektif.
Penduduk yang sebagian bekerja sebagai perajin anyaman bambu menghadapi masalah-masalah kesehatan, air bersih dan administrasi kependudukan. Jatah raskin yang mestinya untuk 46 keluarga ternyata hanya turun untuk 36 keluarga. Akhirnya, mereka sepakat untuk membagi jatah itu untuk 46 keluarga yang berhak menerima raskin.
Petani di Seropan I sangat mengandalkan curah hujan untuk budidaya lahan yang kering dan kurus. Mereka memang sudah mendapatkan fasilitas pompa air dan pipa untuk menaikkan air dari sungai, namun kapasitasnya jauh dari mencukupi.
Sumber: laporan lapangan
Bersama dengan penduduk Karangasem dan Dermojurang (Seloharjo), Jetis dan Kedungjati (Selopamioro), penduduk Nglingseng dan Seropan I adalah subjek program Penguatan Basis Advokasi Kelompok Masyarakat Desa untuk Memperjuangkan Kebijakan Anggaran Publik sejak Mei 2004.


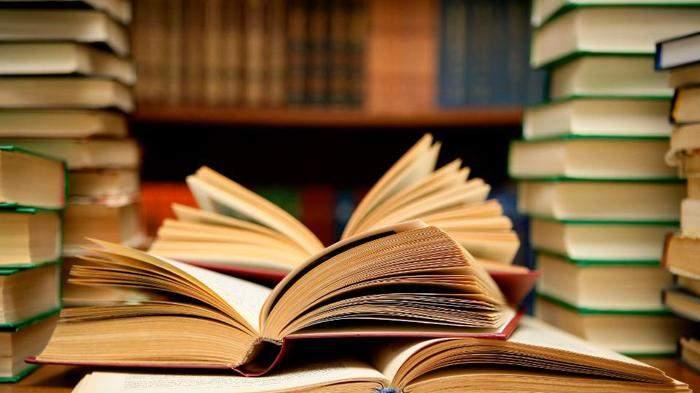




Leave a Reply